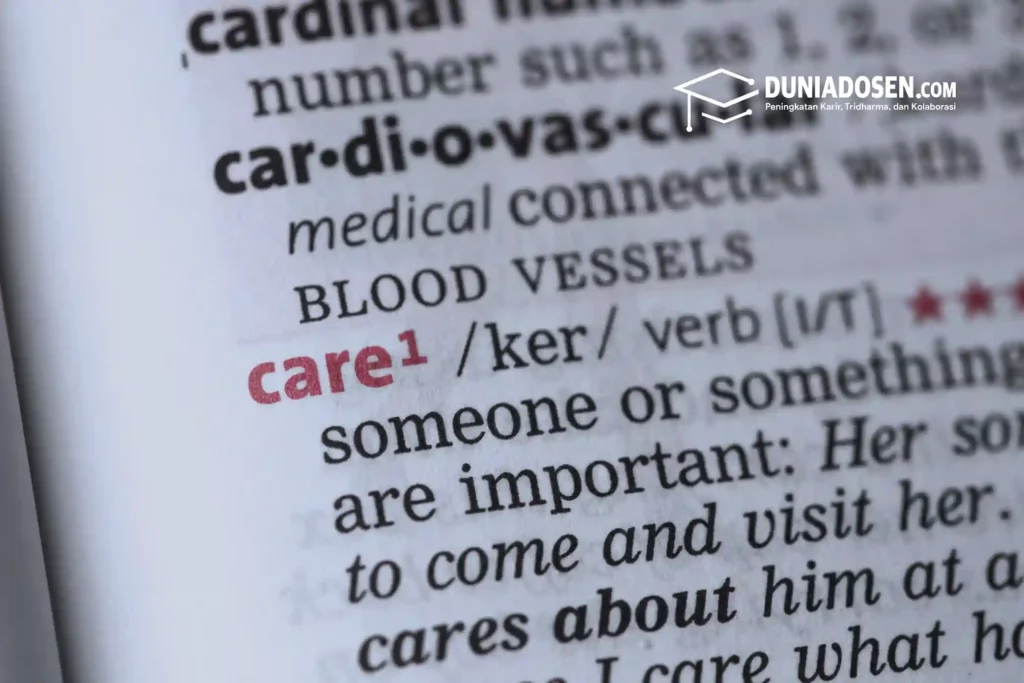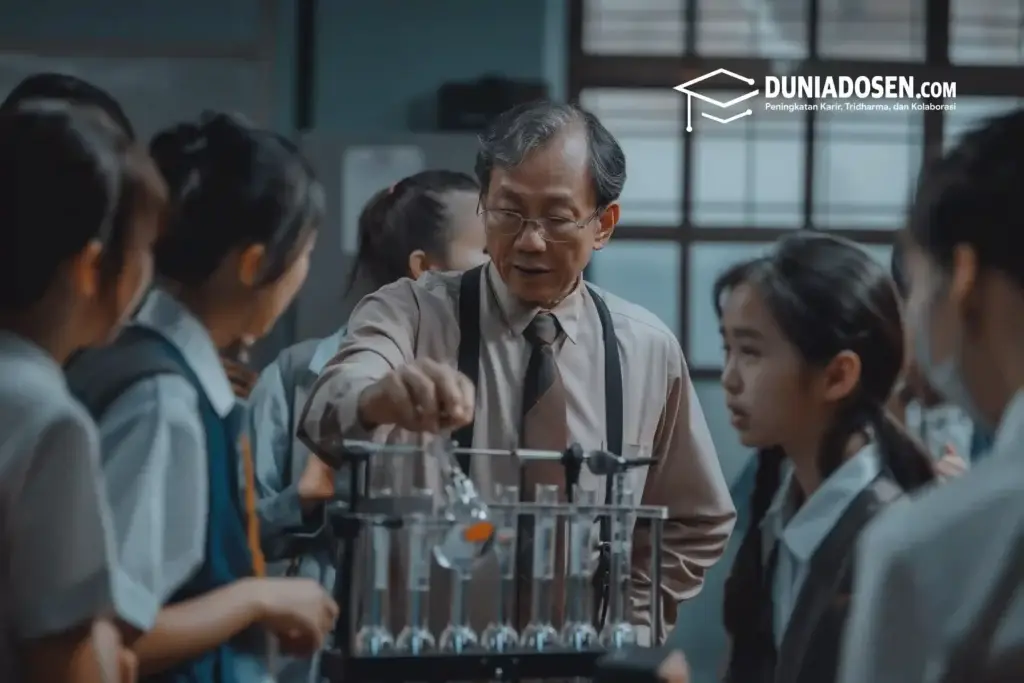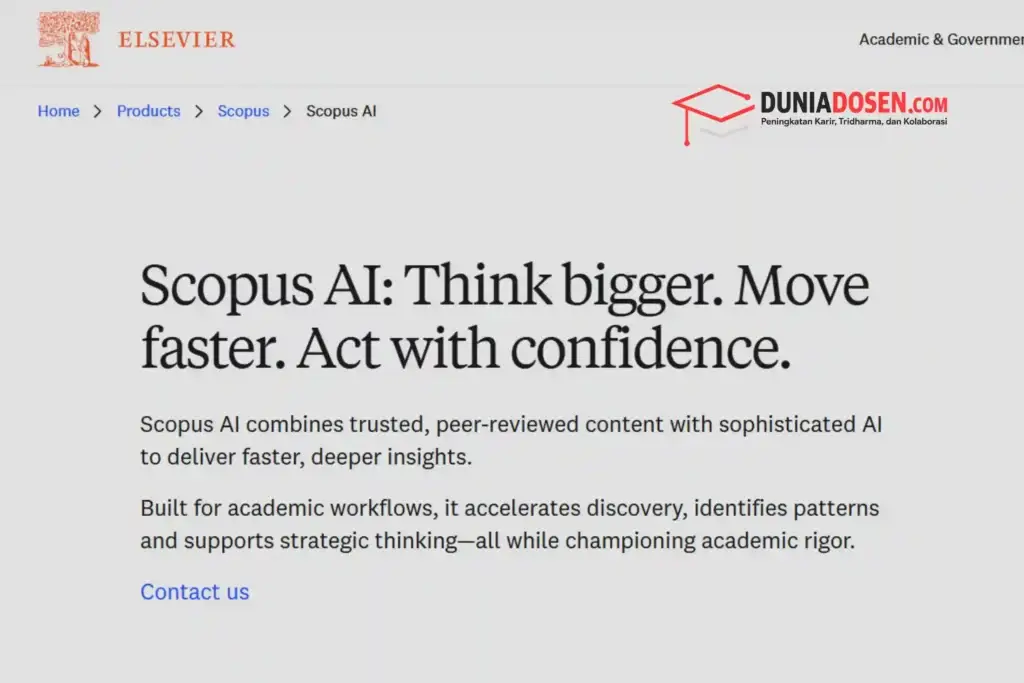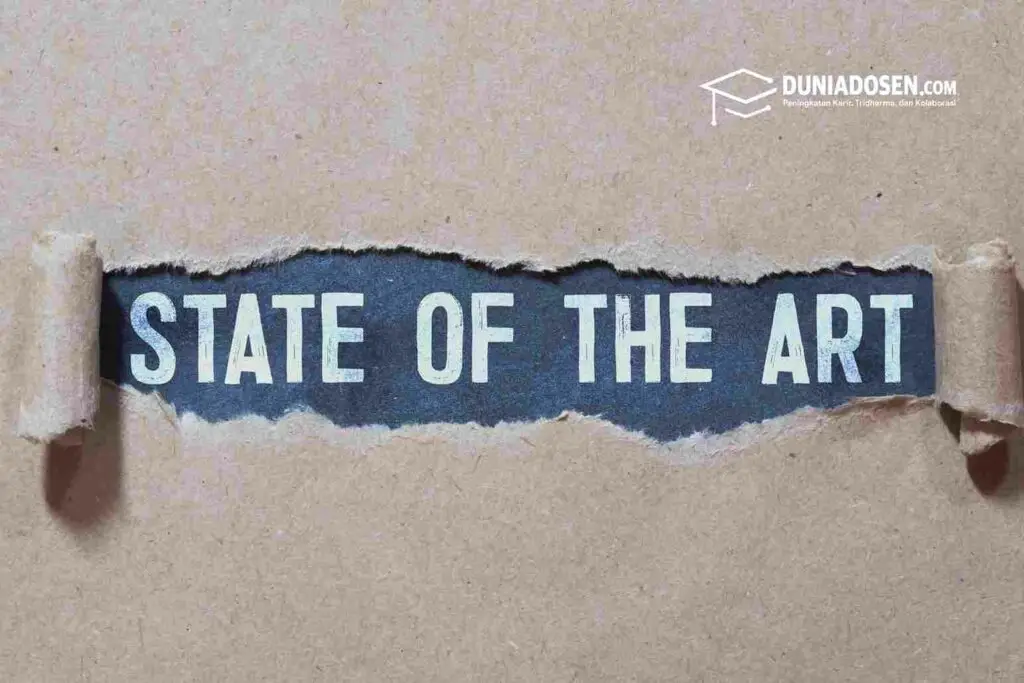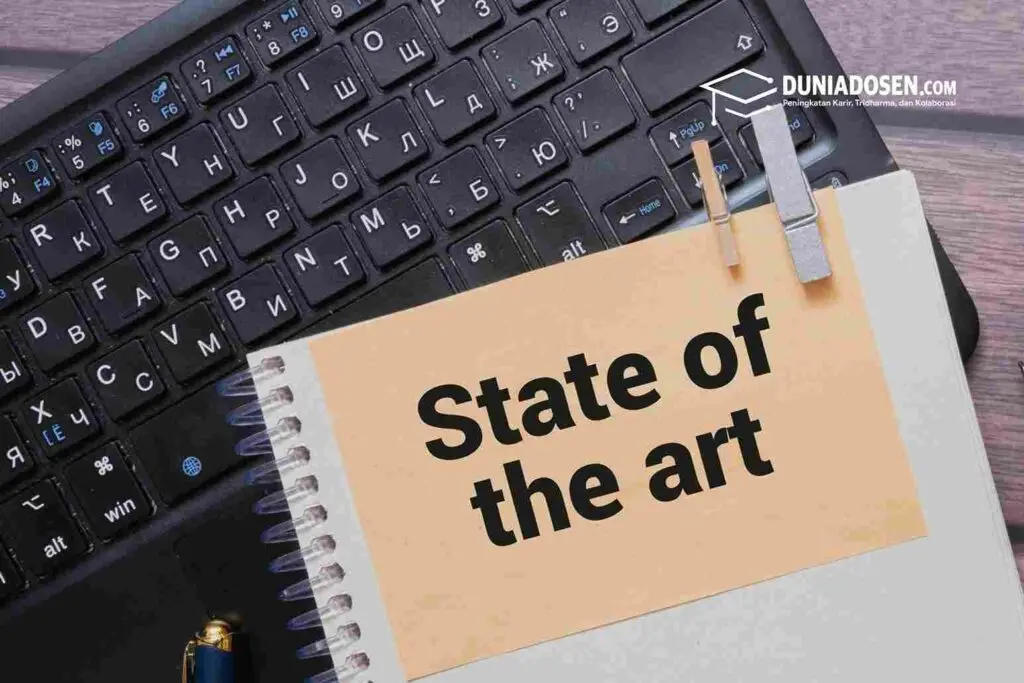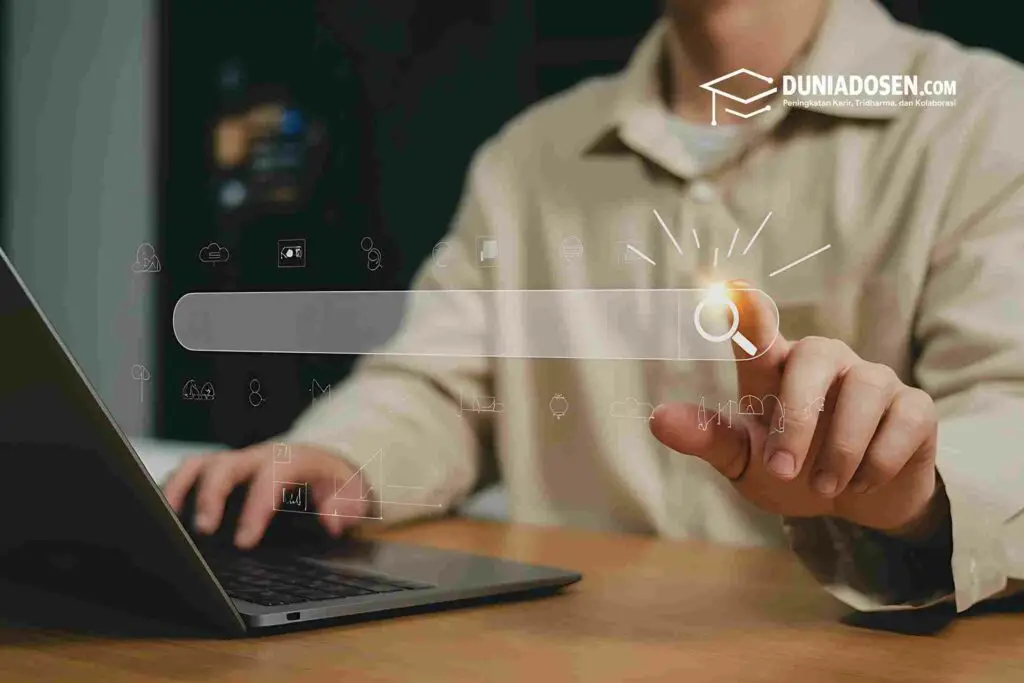Sejak zaman dahulu, manusia senang sekali merekam kegiatan mereka. Mulai dari menggambar di dinding gua, mengukir di batu, menulis di lembar daun atau kertas, hingga mengetik dengan gawai modern mereka. Semua dilakukan demi eksistensialisme diri mereka.
Melalui tulisan, pembaca akan mengetahui kegiatan, isi hati, dan isi pikiran si penulis. Kata-kata dalam tulisan menjadi senjata yang mampu mengundang empati, simpati, hingga inovasi. Apalagi, tulisan juga tidak termakan zaman.
Sudah berapa banyak naskah yang diterjemahkan meski tulisan itu sudah tidak ada lagi penggunanya? Sudah berapa banyak informasi yang terkuak meski manusia dan peradabannya sudah tidak ada dari sekian lama? Tulisan ampuh sebagai penghubung lintas zaman.
Siapa bilang, zaman dahulu, karena belum ada Facebook, manusia tidak bisa update status? Bukankah gambar pada gua dan ukiran di prasasti merupakan bentuk update status penulis yang populer pada masanya? Hebatnya, update status mereka kini menjadi temuan berharga bagi sejarah.
Begitu pun di dunia akademik. Para pencari ilmu senantiasa menuangkan pikiran dan temuan ilmiahnya dalam bentuk tulisan ilmiah. Tulisan-tulisan ini bahkan diharapkan selalu memiliki kebaruan yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada.
Hasil tulisan mereka, biasanya akan terpublikasi di berbagai macam media publikasi ilmiah. Ada yang dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, atau prosiding. Pada hakikatnya, apa pun bentuk publikasinya, kemurnian ide dan gagasan mereka terhadap suatu masalah diharapkan dapat menjadi temuan terbaru dalam menyelesaikan masalah.
Namun, membahas masalah, bukan berarti terbebas dari masalah. Menulis ilmiah kadang kala menjadi tantangan tersendiri. Meski penulis tahu tujuan penulisannya, tahu masalah yang akan dibahasnya, bahkan tahu solusi apa yang hendak ditawarkannya.
Momok di Dunia Publikasi Para Akademisi
Jika diibaratkan, mengembangkan tulisannya menjadi sebuah artikel ilmiah terasa hendak membangun candi. Terlebih, keterbukaan informasi di internet menjadi godaan paling seksi yang sulit untuk dipalingkan. Plagiarisme menjadi momok di dunia publikasi bagi para akademisi.
Upaya “menghajar” plagiarisme pun mulai bermunculan. Beberapa aplikasi anti-plagiarisme diciptakan. Ada yang berbayar, dan ada yang gratis. Dunia akademik seolah tak ingin kecolongan dan memastikan orisinalitas karya ilmiah yang dihasilkan serta dipublikasikan oleh para akademisi.
Baca Juga: Menghadirkan Kesejahteraan di Tengah Kesulitan Ekonomi Saat Wabah Corona
Kualitas publikasi ilmiah di negeri kita pun kini tengah ditingkatkan. Untuk itu, manajemen kualitas dalam dunia perjurnalilmiahan di Indonesia semakin ketat. Sebut saja adanya pemeringkatan melalui Sinta yang mesti melalui proses akreditasi di Arjuna. Hal ini adalah upaya agar pengelolaan publikasi ilmiah di negeri kita menjadi terstandar dan terjaga kualitasnya. Pada akhirnya, pengelola jurnal berusaha mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi sebagai pengejawantahan manajemen kualitas yang dimilikinya.
Dunia perjurnalilmiahan nasional, yang merupakan pintu gerbang dari wajah publikasi ilmiah di Indonesia, memegang peran penting dalam mencitrakan kualitas tulisan para akademisi di Indonesia. Untuk itu, semakin baik manajemennya seharusnya berimplikasi pada semakin bagusnya kualitas artikel yang dipublikasikannya. Semakin tinggi nilai akreditasi jurnalnya, semakin berkualitas semua unsur publikasinya; baik pengelola maupun penulisnya.
Realita ini jelas bukan tanpa masalah. Kemesraan penulis dan pengelola jurnal kadang tidak berjalan dengan baik. Perbedaan sudut pandang dan kebutuhan kadang menjadi pemicunya. Penulis ingin tulisannya terbit demi memenuhi eksistensi beban kerjanya, sedangkan pengelola jurnal melakukan penyaringan naskah demi menjaga kualitas publikasinya agar mendapat eksistensi nilai akreditasi yang baik pula.
Masih ada penulis yang enggan mengirim tulisannya ke jurnal terakreditasi rendah. Baginya, akreditasi jurnal adalah gengsi yang harus dijaga. Jika bisa mempublikasikan tulisan di jurnal terakreditasi tinggi, gengsi juga akan makin tinggi. Sayangnya, hal ini tak dibarengi dengan kualitas naskah si penulis itu sendiri. Terkadang, gengsi mereka tinggi tapi kualitas tulisannya masih memble.
Kemesraan seharusnya terwujud jika setiap unsur dapat memahami satu sama lain. Bagi penulis, bukan asal yang penting terbit. Akan tetapi perlu juga dipahami kompetensi dan kualitas karya tulisnya. Jika masih di bawah kompetensi, maka belajar dan berlatihlah agar kompetensi keilmiahannya dapat tercapai.
Baca Juga: Siapkah Pengajar Indonesia Mengimplementasikan Pembelajaran di Ruang Belajar Virtual?
Jika masih belum memenuhi standar kualitas, maka naskah perlu direvisi sesuai standar kualitas yang ada. Jangan menyalahkan, tapi berkacalah. Jangan bermimpi terlalu tinggi, jika standar yang paling rendah saja malas untuk dipenuhi.
Sedangkan bagi pengelola jurnal, bukan asal menerbitkan. Sistem pemeringkatan semata-mata dibuat untuk menjamin kualitas terbitan. Maka, naskah yang diterbitkan adalah naskah yang memang layak terbit. Bukan karena si penulis mampu bayar berapapun yang diminta oleh si penerbit.
Bukan karena si penerbit memiliki kuasa independen dalam memilih naskah mana yang bisa diterbitkan. Akan tetapi penerbitan naskah ilmiah selalu bermuara pada bacaan yang berkualitas.
Untuk itu, bagi penulis, jangan pernah beranggapan bahwa pengelolaan jurnal bisa dilakukan asal-asalan. Meski masih baru dan belum terakreditasi, bukan berarti haram hukumnya untuk menjaga manajemen kualitas jurnal mereka.
Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Kita, sebagai penulis, mesti memahami bahwa mereka tengah menjalankan dan membiasakan pengelolaan jurnal ilmiah dengan cara yang terstandar dan terbaik. Karena jika pengelolaan sesuatu diawali dengan hal-hal yang belum baik dan asal-asalan, jelas, ini artinya mereka belum siap mengelola sesuatu itu. Buat apa mengelola jika belum siap?
Apalagi urusan publikasi ilmiah. Jika belum siap, sebaiknya jangan dibentuk dan dijalankan. Hal ini karena publikasi ilmiah akan selalu berimplikasi pada wajah pendidikan dan harga diri para akademisinya.
Tentu saja kemesraan antara penulis dan pengelola jurnal ilmiah tidak akan bisa cepat terwujud. Akan tetapi hal ini perlu diupayakan. Bukan hanya sistem manajemennya, tapi juga sumber daya manusianya yang perlu diperbaiki.
Baca Juga: Apakah Dosen Harus Linier? Temukan Jawabannya Disini
Penulis artikel ilmiah haruslah seseorang yang memiliki pola pikir ilmiah yang mumpuni. Jika belum, berlatihlah. Pengelola jurnal ilmiah haruslah mereka-mereka yang mapan dan mumpuni dalam memanajemen serta menerapkan sistem publikasi ilmiah. Jika belum, jangan berikan izin penerbitannya.
Perlu dipahami bahwa semua hasil publikasi yang berkualitas berasal dari penulis-penulis yang kompeten. Untuk itu, paradigma penulisan ilmiah di Indonesia perlu diperkuat bahwa penulisan ilmiah dibuat untuk memecahkan masalah, bukan sekadar untuk eksistensi dan gengsi semata. Agar dapat menggeser paradigma ini, maka diperlukan filterisasi sebelum tulisan ilmiah diterbitkan.
Jika penulis memberikan input yang baik, maka pengelola jurnal harus mampu memastikan output yang baik pula. Kompetensi pengelolaan jurnal ilmiah juga mesti diperhatikan. Bukan asal ada orang yang mau mengelola, tapi memang mereka yang siap mengelola. Penulis dan pengelola jurnal ilmiah mestilah memiliki kompetensi yang seimbang, tidak jomplang.
Keseimbangan kompetensi punggawa publikasi ilmiah dalam proses input maupun output mutlak diperlukan. Hal ini agar tercipta kemesraan persepsi antara penulis dan pengelola jurnalnya. Jangan sampai, penulis merasa kemampuannya setinggi angkasa, pengelola jurnal ilmiah memiliki standar setinggi langit, namun realitanya baik penulis maupun pengelola jurnal hanya melaksanakan lompatan-lompatan kecil di atas tanah.
Jayalah publikasi ilmiah di Indonesia!

Oleh : Nicky Rosadi, S.S.,M.Pd (Dosen Universitas Indraprasta PGRI)