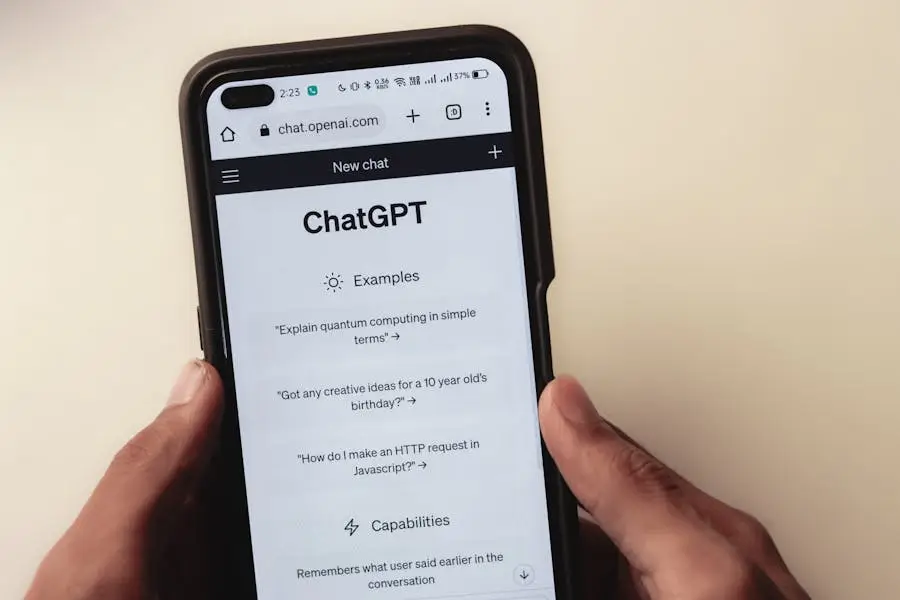Ditulis oleh Ananta Ardyansyah dan Prof. Dra. Sri Rahayu, M.Ed., Ph.D. Tulisan ini menjadi artikel terbaik dalam Lomba Eksplorasi Artikel & Narasi Akademik yang diselenggarakan Penerbit Deepublish dan terpilih untuk dipublikasikan di website resmi Dunia Dosen.
Sejak kemunculannya pada akhir 2022, per Januari 2023, pengguna ChatGPT telah mencapai 100 juta pengguna aktif yang menjadikannya salah satu platform dengan pertumbuhan pengguna tercepat (UNESCO, 2023). Bahkan berdasarkan data per Maret 2025, pengguna ChatGPT telah mencapai 400 juta pengguna (Sinta, 2025).
Angka tersebut hampir mencapai 60% dari pangsa pasar generatif AI di dunia. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan betapa cepatnya internalisasi teknologi generatif AI, khususnya generative pre- trained transformer (GPT) dalam masyarakat.
Popularitas ChatGPT sebagai pionir AI generatif, khususnya GPT, turut mendorong lahirnya platform serupa seperti Claude, Grok AI, Meta AI, dan DeepSeek. Selain itu, terdapat juga generatif AI lainnya yang muncul dengan fokus yang berbeda-beda, seperti Midjourney dan DALL-E yang berfokus pada pembuatan gambar serta Google VEO dan Sora yang berfokus pada pembuatan video.
Sedemikian pesatnya perkembangan AI saat ini, konten yang dihasilkan AI hampir tidak dapat dibedakan dengan apa yang dibuat manusia. Sayangnya, perkembangan pesat ini tidak dibarengi dengan regulasi yang baik.
Penelitian Schiff (2022) menunjukkan bahwa kebijakan terkait AI saat ini cenderung teoritis dan kurang bukti empiris serta sering kali mengabaikan aspek pendidikan dan etika. Hal tersebut diperkuat laporan UNESCO yang menunjukkan per Januari 2023 hanya negara China saja yang memiliki kebijakan terkait generative AI.
Sementara itu, kebijakan Indonesia terkait AI hanya berupa garis besar penggunaan dan pengembangan yang tercantum pada “Indonesia National Strategy for Artificial Intelligence 2020−2024” (Sekretariat Nasional Kecerdasan Artifisial Indoneisa, 2020).
Kebijakan lebih komprehensif kemudian muncul pada akhir 2024, tapi masih terbatas pada perguruan tinggi (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024). Padahal, AI masih memiliki potensi dapat memberikan respon yang salah dan berbagai isu terkait penggunaannya (Yu, 2023).
Tanpa kebijakan yang tepat, pesatnya perkembangan AI dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diantisipasi.
Tak dapat dipungkiri, selain membawa perubahan yang positif, AI memiliki potensi dampak negatif dalam berbagai hal, termasuk pendidikan. Pendidikan merupakan bagian krusial dalam hidup seorang manusia.
Melalui elemen yang bernama “pendidikan” seseorang dapat melatih fungsi kognitifnya dan berbagai hal lainnya, sehingga dapat mencapai potensi utuhnya sebagai manusia, yaitu makhluk yang berakal. Namun, apa jadinya jika adanya teknologi bernama “kecerdasan buatan” malah menggantikan “kecerdasan” manusia itu sendiri?.
Tentunya hal tersebut adalah kemungkinan terakhir yang ingin dibayangkan umat manusia. Tapi nyatanya, sebagai akibat lambatnya kebijakan terkait AI, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan AI di dunia pendidikan, seperti plagiasi, miskonsepsi, dan penyebaran informasi yang salah (Joyce, 2023).
Bahkan, kini terdapat banyak kasus dimana konten misinformasi diproduksi menggunakan AI (Fatimah et al., 2024; Shao et al., 2018; Xu et al., 2023).
Bahkan, penelitian terbaru dari MIT menunjukkan bahwa penggunaan GPT dapat mengurangi keterlibatan kognitif, kemampuan memori, aktivitas otak, dan rasa kepemilikan terhadap hasil pekerjaan (Kosmyna et al., 2025).
Dengan demikian, AI tidak hanya menghilangkan potensi manusia untuk belajar, tapi juga dapat memberikan pembelajaran yang salah bagi manusia yang belajar. Lantas bagaimana kita seharusnya memperlakukan AI? Pembahasan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam AI in education (AIEd).
Perspektif Ki Hadjar Dewantara dalam Memandang Pendidikan
Ukuran baik buruk ini tentunya akan berbeda pada setiap kondisi, negara, dan konteks lainnya. Dengan demikian, integrasi AI dalam masyarakat satu dengan masyarakat lainnya mungkin berbeda. Kemudian, bagaimana implementasi yang paling bijak dalam konteks pendidikan di Indonesia? Untuk memahami ini, penting untuk memperhatikan pandangan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara (KHD).
KHD merupakan seorang bangsawan Jawa yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. KHD merupakan pionir dalam dunia pendidikan Indonesia dengan berbagai kontribusi pemikiran yang begitu komprehensif.
KHD tidak hanya memberikan prinsip utama guru dalam mengajar, tetapi juga berbagai pandangan lainnya, seperti bagaimana manusia memperoleh ilmu, bagaimana pendidikan itu seharusnya dilaksanakan, dan apa tujuan sebuah pendidikan.
Menurut Ki Hadjar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah mencapai keutuhan manusia, memenuhi kebutuhan dari jiwa dan raganya (Dewantara, 1962). Acuannya tentu saja ada pada konsep lain yang disebutkan KHD, yaitu Panca Dharma. Panca Dharma berisi tentang kodrat alam (nature), kemerdekaan (freedom), kebangsaan (nationalism), kebudayaan (culture), dan kemanusiaan (humanity).
Melalui pendidikan, seseorang akan mengalami tri ngo, yaitu ngerti (mengerti), ngroso (merasakan), dan nglakoni (menjalankan). Jika dipahami secara bersama, artinya pendidikan bertujuan untuk memahami dan merasakan di sekitar kita, sehingga dapat melakukan kebaikan untuk masyarakat (Sugiharto, 2021).
Tidak heran, jika dalam pengajarannya, KHD menekankan budi pekerti dimana sebuah aksi dilakukan berdasarkan kesatuan pemikiran, rasa, dan keinginan.
Selain menekankan tujuan dari sebuah pembelajaran, KHD juga memaparkan tiga proses dalam pembelajaran yang dikenal sebagai tri N, yaitu niteni, niroke, dan nambahi. Niteni berarti mengingat yang mana proses ini umum dilakukan seorang siswa dalam pembelajaran dimana mereka mengingat informasi.
Kedua, niroke yang berarti meniru apa yang telah mereka pelajari pada langkah sebelumnya. Konsep terakhir, yaitu nambahi yang artinya memperkaya dimana seorang siswa mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran (Dewantara, 1977).
Dari sisi guru, KHD memperkenalkan sistem “among” dimana melalui sistem ini, seorang guru diposisikan sebagai orang tua yang mendukung pembelajaran aktif anaknya.
Dalam pembelajaran, guru hendaknya momong (mengasuh), among (membimbing), dan ngemong (mendukung), sehingga siswa dapat mengembangkan pengetahuannya secara mandiri.
Selain itu, gagasan KHD yang tidak kalah terkenal, yaitu “ing ngraso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” dimana slogan ini menggambarkan peran guru dalam mendukung pembelajaran siswa, khususnya pada aspek kepemimpinan (Supriadi et al., 2025).
Guru hendaknya menjadi contoh, membangkitkan semangat serta inisiatif, dan mendorong siswa. Lebih lanjut, pemikiran-pemikiran tersebut secara tidak langsung menunjukkan keselarasan pemikiran cendekiawan Indonesia dengan tokoh global, khususnya dalam teori pembelajaran konstruktivisme, seperti John Dewey dan Lev Vygostky.
Keseluruhan pemikiran dari KHD ini kemudian ia tuangkan dalam sekolah Taman Siswa yang tidak hanya menjadi manifestasi fisik dari pemikirannya, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda (Radcliffe, 1971).
Oleh karena itu, Ki Hadjar Dewantara menjadi tokoh yang pemikirannya penting digunakan dalam memandang kebijakan pendidikan di Indonesia. Meskipun, tidak mudah dalam pelaksanaannya, filosofi pendidikan dari KHD masih relevan hingga sekarang dan dapat diimplementasikan (Ferary, 2021).
GPT dalam Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara
Dengan set data yang begitu masif dan kemampuan berpikir yang tinggi, apakah GPT otomatis merupakan seorang guru yang baik? Untuk memastikan hal ini penting untuk menilai terlebih dahulu apakah GPT seorang murid yang baik.
Dalam sebuah pendidikan, setidaknya ada dua aspek penting agar sebuah pembelajaran dapat berlangsung, yaitu murid dan guru. Dua elemen tersebut saling berhubungan dan penting keberadaan utuh keduanya agar sebuah proses pendidikan dapat berlangsung?.
Dalam kacamata KHD, setiap murid melakukan pembelajaran untuk menjadi pribadi yang merdeka dan utuh (mencapai potensi penuhnya). Dalam prosesnya, siswa mengalami dua hal besar yang berkaitan dengan bagaimana seseorang belajar dan bagaimana seseorang menggunakan apa yang dipelajarinya.
Menurut KHD, seseorang yang belajar mengalami tiga proses, yaitu niteni, niroke, dan nambahi.
GPT tentunya dapat mengalami proses niteni jika diberikan data yang cukup, bahkan dapat melakukan proses pengamatan (identifikasi dan memahami) dengan baik. Berbagai penelitian telah menunjukkan hal demikian dimana GPT mampu memahami dan meringkas sesuatu dengan baik.
Performa GPT dalam tugas tersebut secara tidak langsung menunjukkan kemampuan GPT dalam niteni. Kemampuan tersebut kemudian dimanifestasikan dalam “nirokke” dimana GPT dapat membuat konten serupa setelah proses mengamati yang dilakukannya.
Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa respons yang diberikan GPT merupakan tiruan yang sempurna, menggarisbawahi kemampuannya dalam menirukan sesuatu.
Namun, ketika sampai pada tahap ketiga, yaitu “nambahi”, kita mungkin akan sampai pada pertanyaan “apakah GPT mampu membuat suatu hal yang sepenuhnya baru?” Dalam “nambahi” terdapat nuansa kreatif dan inovatif yang tidak hanya sekedar meniru. “nambahi” memiliki makna dimana seseorang menyumbangkan ide yang sepenuhnya baru bagi masyarakat. Di sini lah keterbatasan GPT tampak.
Pada dasarnya, GPT dilatih berdasarkan konten yang sudah ada dalam masyarakat. Hasil responsnya merupakan modifikasi dan penataan ulang dari sesuatu yang sudah ada. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa GPT tidak sepenuhnya menyelesaikan tahapan pembelajaran yang dikemukakan oleh KHD.
Tentunya, tanpa proses belajar yang utuh, GPT juga tidak mengalami internalisasi apa yang dipelajarinya. Melalui pembelajaran, berdasarkan KHD, seseorang akan mengalami ngerti, ngroso, dan nglakoni. Keseluruhan proses tersebut menggambarkan seorang siswa menggunakan apa yang dipelajarinya. Ngerti memiliki arti memahami dan tentu saja GPT mampu mengalami proses ini.
Namun, pada ngroso akan muncul pertanyaan, apakah GPT dapat benar-benar merasakan? Hakikatnya, AI tidak benar-benar merasakan emosi, seperti apa yang dilakukan manusia. Tapi, AI mampu mengenali, menstimulasi, dan merespons emosi manusia karena dirancang sedemikian rupa, sehingga terasa dapat merasakan emosi.
Terlepas dari pemahaman bahwa AI tidak dapat merasakan emosi, AI berdampak pada emosi manusia secara positif dan negatif (Pantano & Scarpi, 2022). Selanjutnya, pada aspek nglakoni yang dimaknai sebagai aktualisasi pemahaman mereka dalam kehidupan, GPT jelas tidak mampu melakukannya.
Sederhananya, bagaimana sesuatu yang tidak hidup dapat mempraktikkan sesuatu dalam kehidupan?. Dengan demikian, GPT tidak mampu melakukan internalisasi apa yang dipelajarinya dalam kehidupan dari perspektif Ki Hadjar Dewantara.
Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa GPT bukan seorang pembelajar atau murid yang utuh. GPT tidak mengalami proses pembelajaran secara lengkap dan tidak sepenuhnya menggunakan apa yang dipahaminya.
Tidak adanya dua proses tersebut menjadikan GPT tidak mampu mencapai tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh KHD. Lebih lanjut, hal ini membawa kesimpulan bahwa GPT tidak mencapai Panca Dharma yang disebutkan oleh KHD.
Jika bukan murid yang seutuhnya, apakah GPT merupakan guru yang seutuhnya? Mungkin saja kita sudah memiliki jawaban akan hal ini. Namun, kajian dari sudut pandang guru menurut KHD menarik untuk ditelisik.
Dari sisi guru, terdapat dua hal penting yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu prinsip pendidik dan cara pendidik dalam menempatkan diri. Seperti yang telah dijelaskan di atas, seorang pendidik, menurut KHD memiliki tiga prinsip, yaitu momong, among, dan ngemong. Prinsip ini menjelaskan apa peran guru dalam pembelajaran, seorang guru secara singkat perlu mengasuh, membimbing, dan mendukung.
Ketiga prinsip tersebut secara dasar sangat komprehensif dan berkaitan erat dengan perasaan yang sekali lagi tidak sepenuhnya benar-benar dipahami oleh AI. Jadi, tentu saja GPT tidak memiliki prinsip-prinsip guru yang dicanangkan oleh KHD.
Lebih lanjut hal ini berhubungan dengan bagaimana seorang pendidik menempatkan diri yang secara singkat harus dapat memberikan teladan, memberikan semangat, dan mendorong dari belakang. Untuk melakukan hal tersebut, seorang guru perlu hadir secara menyeluruh dalam perkembangan seorang murid yang lagi-lagi tidak dapat dilakukan oleh GPT.
Penutup
Pada dasarnya, filosofi pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara merupakan filosofi yang humanistis dan relevan dengan nilai-nilai lokal. Sementara itu, AI dan GPT datang dengan dominasi nilai barat dan pendekatan yang logis.
Jadi, tidak heran melalui kajian ini dapat dipahami bahwa GPT bukanlah seorang murid, maupun guru yang utuh dalam kacamata Ki Hadjar Dewantara. GPT tidak mampu menjadi murid karena bukan pembelajar sejati yang megalami proses niteni, nirokke, dan nambahi secara sempurna serta tidak mengalami internalisasi pemikiran (ngerti, ngrasane, dan nglakoniI).
Maka jelas saja, jika bukan seorang murid yang utuh, GPT juga tidak mampu menjadi guru yang utuh. Guru utuh memahami prinsip pengajaran (monong-among-ngemong) dan bagaimana cara menempatkan diri (ing ngraso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani). Oleh karena itu, GPT tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran murid dan guru seutuhnya.