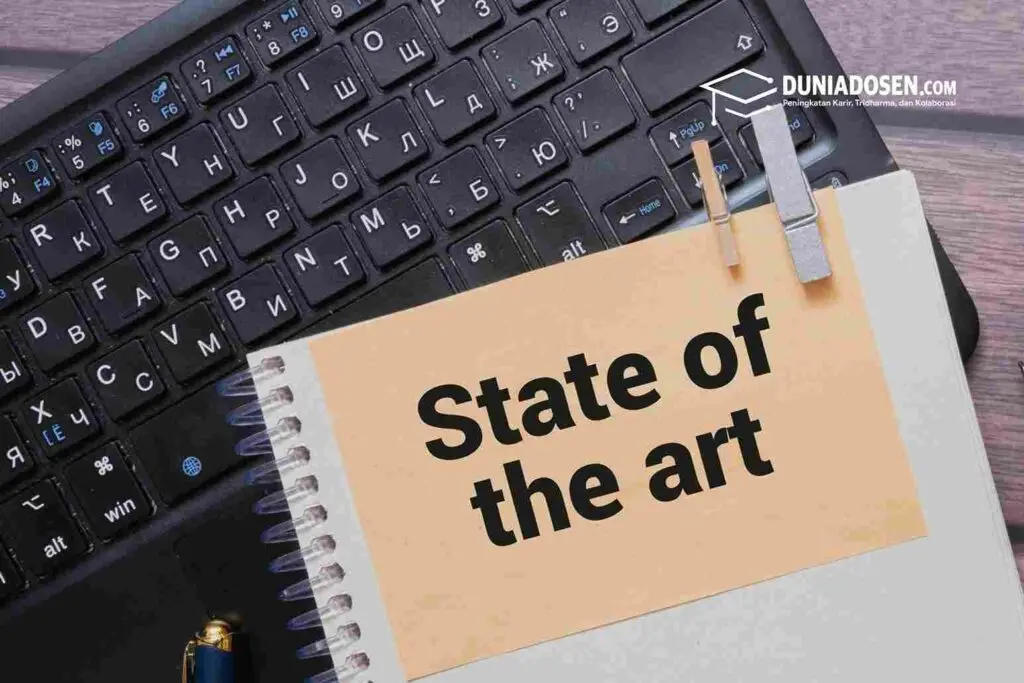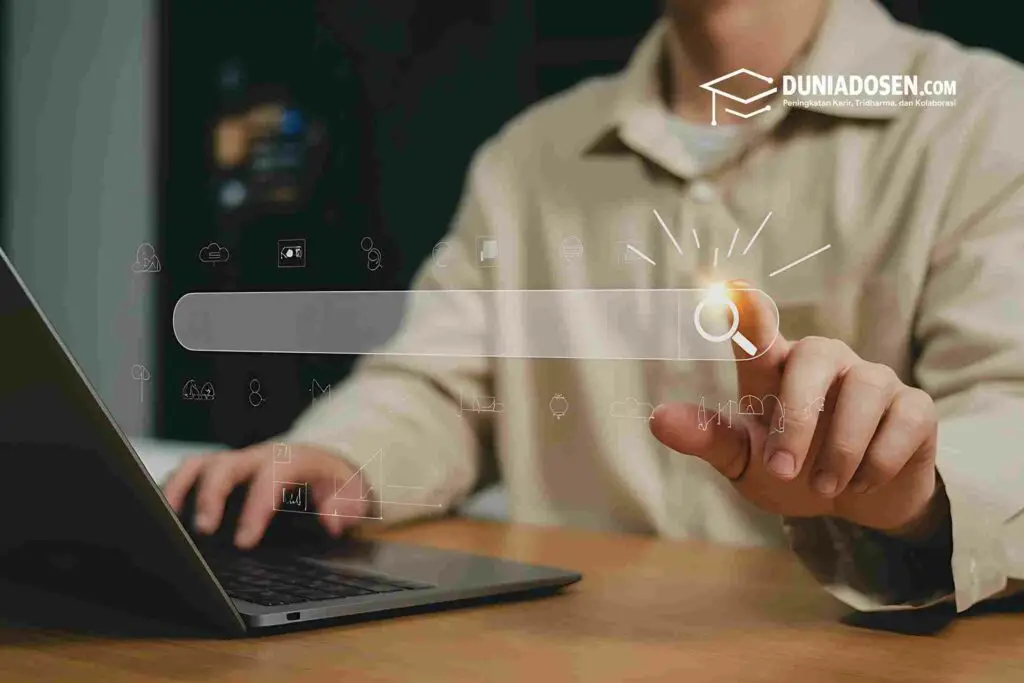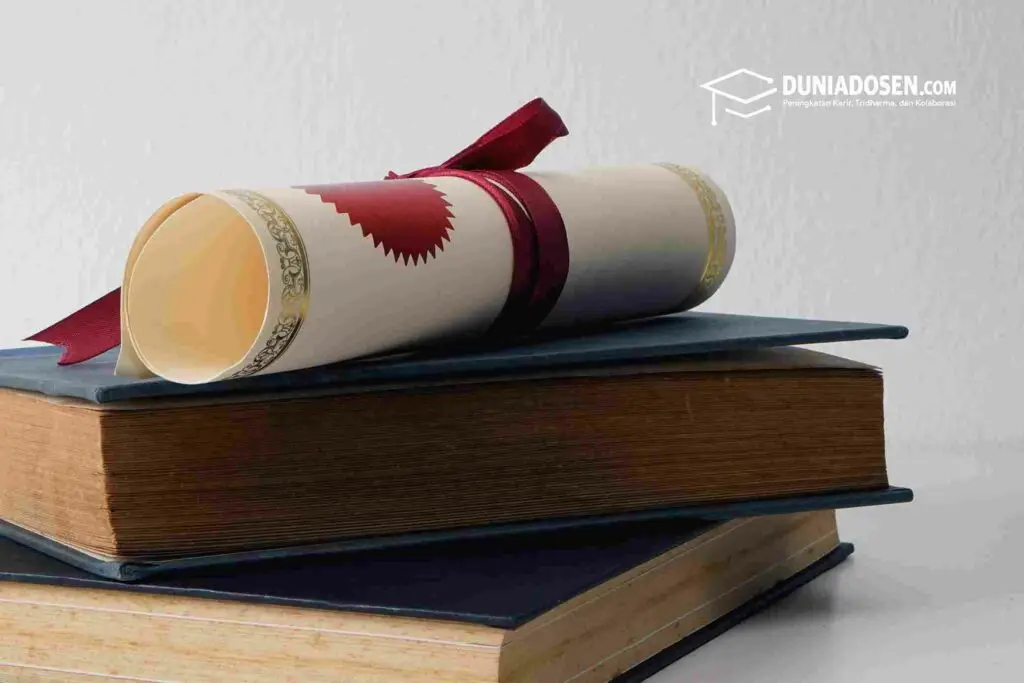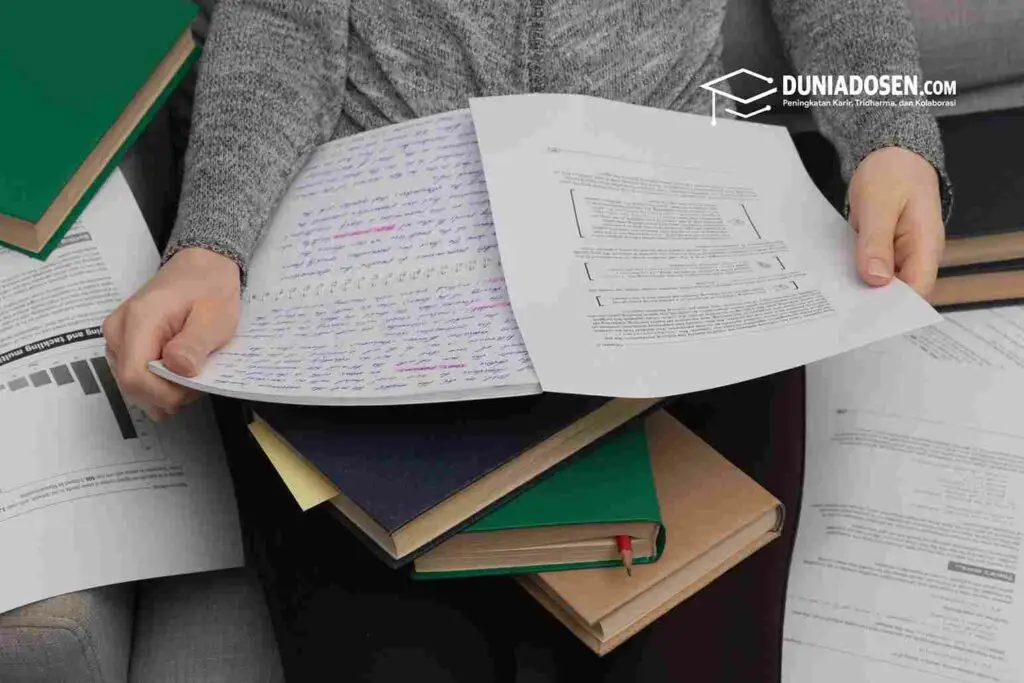Ditulis oleh Hardika Khusnuliawati, M.Kom. Tulisan ini menjadi artikel terbaik dalam Lomba Eksplorasi Artikel & Narasi Akademik yang diselenggarakan Penerbit Deepublish dan terpilih untuk dipublikasikan di website resmi Dunia Dosen.
Daftar Isi
Toggle‘Ketika Belajar Mulai Digerakkan oleh Kecerdasan Buatan
Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kekuatan transformatif dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari industri, kesehatan, hingga keuangan, semuanya terdampak oleh kehadiran teknologi berbasis AI. Tidak terkecuali sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang kini memasuki fase digitalisasi lanjutan. Mahasiswa saat ini tidak lagi hanya mengandalkan dosen, buku, atau perpustakaan sebagai sumber belajar, tetapi juga pada chatbot cerdas seperti ChatGPT.
Dengan sekali ketik, mereka bisa mendapatkan ringkasan materi, membuat rancangan artikel ilmiah, hingga menjawab tugas maupun soal ujian. Kecepatan dan efisiensi ini tentu menguntungkan dari segi akses dan waktu.
Namun, muncul pertanyaan yang lebih mendalam yaitu apakah AI membantu memperkuat proses belajar atau justru mengambil alih kemampuan berpikir mahasiswa? Apakah kecanggihan teknologi justru melemahkan nalar dan menurunkan daya kritis generasi akademik?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika, tetapi menyentuh esensi dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan hanya soal transfer informasi, melainkan juga tentang membentuk manusia yang berpikir kritis, bernalar logis, dan memiliki integritas etika.
Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana AI berdampak terhadap dinamika belajar di perguruan tinggi, dan bagaimana institusi serta kebijakan publik merespons perubahan ini.
Temuan Studi MIT: Saat Mesin Menggantikan Aktivitas Otak
Salah satu penelitian paling relevan dalam diskusi ini datang dari MIT Media Lab. Pada tahun 2024, mereka melakukan studi eksperimental terhadap 54 peserta yang diminta menulis esai dengan tiga cara berbeda meliputi penggunaan kemampuan otak sendiri tanpa bantuan teknologi, penggunaan Google untuk mencari referensi, dan penggunaan ChatGPT untuk menyusun jawaban.
Selama proses menulis, aktivitas otak mereka dipantau menggunakan alat EEG (electroencephalogram). Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan ChatGPT memiliki tingkat aktivitas otak paling rendah.
Mereka cenderung pasif, tidak menunjukkan pola keterlibatan kognitif yang mendalam. Esai yang mereka hasilkan memang terlihat rapi secara teknis, tetapi dinilai miskin dari sisi orisinalitas, gaya bahasa, dan kedalaman argumen.
Fenomena ini kemudian disebut sebagai metacognitive laziness, sebuah kondisi di mana seseorang enggan berpikir lebih lanjut karena sudah terbiasa mengandalkan mesin. Dengan kata lain, AI berpotensi mengurangi kapasitas berpikir reflektif manusia jika digunakan tanpa kendali.
Sebaliknya, peserta yang tidak menggunakan bantuan AI justru menunjukkan aktivitas otak lebih tinggi dan menghasilkan karya tulis yang lebih kreatif serta variatif.
Perspektif Global dan Lokal terhadap Transformasi Pendidikan
Kekhawatiran terhadap dampak penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan tidak hanya muncul dari kalangan akademisi dan pendidik, tetapi juga dari berbagai pengamat teknologi global. Media internasional seperti The Guardian, TIME, hingga The Atlantic telah mempublikasikan laporan dan opini yang menyoroti konsekuensi jangka panjang dari adopsi AI, khususnya dalam proses belajar mengajar di jenjang pendidikan tinggi.
Salah satu artikel yang cukup berpengaruh berjudul “Don’t Ask What AI Can Do for Us, Ask What It’s Doing to Us” mengungkapkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat melemahkan kapasitas berpikir manusia.
Para pakar dalam artikel tersebut memperkenalkan istilah dependency syndrome untuk menggambarkan kondisi ketika individu menjadi terlalu bergantung pada solusi instan yang disediakan mesin, sehingga mengabaikan proses berpikir kritis yang esensial dalam pendidikan. Ini merupakan bentuk kemunduran kognitif yang tidak terlihat secara langsung, tetapi berdampak besar dalam jangka panjang.
Fenomena ini juga mulai terasa di Indonesia. Banyak dosen melaporkan bahwa mereka semakin sering menerima tugas mahasiswa yang terlalu sempurna, baik dalam struktur tulisan, penggunaan tata bahasa, maupun narasi logis yang rapi.
Namun, hasil tersebut justru tidak mencerminkan kemampuan asli mahasiswa berdasarkan observasi sebelumnya di kelas. Gaya penulisan yang terlalu formal dan berjarak sering kali menjadi penanda bahwa konten tersebut dihasilkan atau setidaknya dibantu oleh alat seperti ChatGPT.
Lebih jauh lagi, seorang dosen di Malang menuturkan kekhawatirannya terhadap mahasiswa baru yang kini kesulitan menyusun kalimat secara logis dan padu. Mereka cenderung menghindari membaca sumber referensi dan lebih memilih mengandalkan jawaban instan dari AI tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran informasi.
Laporan serupa juga datang dari berbagai kampus, yang mencatat peningkatan penggunaan generative AI oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, bahkan ketika mereka belum memahami konsep dasar dari materi yang diberikan.
Akibatnya, proses belajar bergeser dari aktivitas pemahaman dan eksplorasi menjadi sekadar menyalin jawaban. Hal ini tidak hanya mengikis kemampuan riset mandiri, tetapi juga melemahkan literasi informasi serta kemampuan kritis dalam memeriksa fakta.
Fenomena ini menunjukkan meskipun AI memiliki potensi besar dalam mendukung pembelajaran, penggunaan yang tidak bijak dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kualitas pendidikan tinggi.
Jika tidak segera ditangani secara sistemik, praktik semacam ini berpotensi mengikis nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas yang menjadi fondasi dari dunia pendidikan. Tanpa adanya intervensi yang tepat baik dari lembaga pendidikan maupun pemerintah, integritas akademik bisa runtuh secara perlahan dan sistematis.
Menolak atau Merangkul AI, Kampus dan Dosen Hadapi Titik Kritis
Perguruan tinggi saat ini berada di titik kritis dalam merespons kehadiran kecerdasan buatan (AI) dalam dunia akademik. Teknologi seperti ChatGPT, Bing Copilot, dan berbagai platform generatif lainnya telah masuk ke ruang-ruang pembelajaran, menimbulkan dilema besar yaitu apakah AI perlu ditolak, dibatasi, atau justru diintegrasikan secara aktif dalam sistem pendidikan?
Secara global, sebagian institusi pendidikan tinggi telah mengambil langkah progresif dengan mengadopsi AI secara terstruktur dan terkendali. Mereka membuat pedoman penggunaan teknologi AI, menyusun kurikulum yang memasukkan literasi AI sebagai kompetensi dasar, dan melatih dosen agar mampu memanfaatkan AI dalam pengajaran maupun evaluasi.
Dalam pendekatan ini, AI dianggap sebagai alat bantu yang dapat memperkuat proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi, dan memperluas cakupan sumber belajar.
Namun, tidak semua institusi memiliki kesiapan yang sama. Ada pula kampus yang memilih pendekatan konservatif dengan membatasi atau bahkan melarang penggunaan AI, terutama dalam tugas-tugas berbasis esai dan ujian daring.
Alasan utama di balik kebijakan ini adalah kekhawatiran akan penyalahgunaan AI oleh mahasiswa untuk melakukan plagiarisme atau menyelesaikan tugas tanpa memahami substansi materi. Beberapa kampus bahkan mulai mengembangkan perangkat lunak pendeteksi AI-generated content, meski teknologi ini sendiri belum sepenuhnya akurat dan masih dalam tahap pengembangan.
Dalam konteks ini, pendekatan paling realistis bukanlah pelarangan mutlak atau penerimaan total, melainkan membangun literasi teknologi dan etika digital yang kuat. Mahasiswa perlu dibekali pemahaman menyeluruh tentang bagaimana AI bekerja, di mana batasannya, serta apa konsekuensi akademik dan etis dari penggunaannya. Penggunaan AI harus diarahkan untuk mendukung kreativitas dan proses berpikir, bukan menggantikannya.
Misalnya, ChatGPT bisa menjadi alat bantu dalam proses brainstorming, menyusun kerangka awal tulisan, atau merangkum literatur. Namun, mahasiswa tetap dituntut untuk melakukan analisis, dan menyusun argumentasi dengan nalar mereka sendiri. AI seharusnya menjadi mitra intelektual, bukan pengganti otak.
Di sisi lain, peran dosen juga perlu mengalami transformasi signifikan. Di era AI, dosen tidak lagi sekadar menjadi penyampai materi atau pemberi tugas, melainkan harus bertindak sebagai kurator pengetahuan, fasilitator diskusi kritis, dan pembimbing etika digital.
Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya tahu cara menggunakan AI, tetapi juga tahu kapan harus menggunakannya dan kapan harus mengandalkan kemampuan intelektual mereka sendiri.
Dosen juga harus aktif dalam merancang penilaian yang menuntut pemikiran orisinal dan tidak dapat dengan mudah diselesaikan oleh AI, misalnya tugas berbasis refleksi pribadi, studi kasus kontekstual, atau debat terbuka. Hal ini dapat mendorong mahasiswa untuk tetap berpikir kritis dan tidak tergoda menggunakan AI secara instan tanpa pemahaman mendalam.
Dengan pendekatan yang seimbang antara regulasi, edukasi, dan adaptasi teknologi, AI dapat dimanfaatkan secara positif di perguruan tinggi. Tantangannya bukan pada ada atau tidaknya AI, tetapi pada kesiapan kampus dan dosen dalam menyikapinya secara cerdas dan bertanggung jawab.
Peran Strategis Negara dalam Mengarahkan Kebijakan Penggunaan AI di Pendidikan Tinggi
Dalam era digital yang ditandai dengan penetrasi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor, pendidikan tinggi turut mengalami perubahan besar dalam pola pembelajaran dan interaksi akademik. Teknologi seperti ChatGPT, Copilot, dan generative AI lainnya kini telah digunakan secara luas oleh mahasiswa untuk membantu menyusun tugas, mencari referensi, bahkan membentuk kerangka berpikir dalam berbagai konteks akademik.
Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan, muncul tantangan serius yaitu bagaimana memastikan penggunaan AI di dunia kampus tetap sejalan dengan nilai-nilai akademik, tanpa menggerus kemampuan berpikir kritis mahasiswa?
Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis sebagai pengarah kebijakan makro. Tidak cukup jika upaya pengendalian hanya dibebankan kepada pihak kampus. Pemerintah perlu mengambil peran aktif untuk membentuk kerangka regulasi dan ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap berpijak pada prinsip etika dan integritas akademik.
Beberapa langkah strategis dapat diambil pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan ini. Pertama, melalui penguatan literasi digital nasional, negara perlu mendorong kurikulum yang tidak hanya menekankan kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga mengajarkan etika digital serta kesadaran kritis dalam memanfaatkan AI. Literasi ini penting agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengelola teknologi secara bertanggung jawab.
Kedua, pemerintah perlu menyusun regulasi dan kode etik nasional terkait penggunaan AI dalam pendidikan. Aturan ini dapat mencakup batasan penggunaan AI dalam tugas akademik, prinsip transparansi dalam penggunaan teknologi, serta sanksi terhadap penyalahgunaan yang terbukti melanggar integritas akademik.
Ketiga, penting adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor teknologi, dan lembaga riset. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, sehat, dan bertanggung jawab terhadap tantangan transformasi digital.
Terakhir, negara harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap arah pendidikan negara. Arah pendidikan sebaiknya tidak semata-mata berorientasi pada kesiapan menghadapi industri 4.0 dan 5.0, tetapi selaras dengan tujuan luhur pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh baik intelektual, spiritual, dan moral.
Dengan membangun kerangka kebijakan yang komprehensif dan inklusif, negara dapat memastikan bahwa AI menjadi alat bantu yang cerdas dan etis dalam proses pendidikan—bukan sebagai pengganti pemikiran manusia, melainkan sebagai mitra dalam membangun peradaban yang berpikir dan bertanggung jawab.
Kesimpulan: Mengembalikan Pikiran ke Ruang Belajar
AI dalam pendidikan tinggi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun, realitas ini membawa konsekuensi besar jika tidak dikelola secara bijak. Studi MIT, opini global, dan fenomena lokal menunjukkan bahwa penggunaan AI secara tidak terkendali dapat menurunkan kualitas berpikir mahasiswa, memicu kecurangan akademik, dan bahkan merusak integritas pendidikan secara menyeluruh.
Menghadapi tantangan ini, solusi yang dibutuhkan tidak cukup bersifat teknis atau individual. Diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif. Kampus memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong berpikir kritis dan penggunaan AI secara etis.
Mahasiswa sebagai pengguna utama teknologi harus dibekali dengan literasi AI, kesadaran etika, dan tanggung jawab intelektual. Namun, yang paling krusial, negara harus hadir secara aktif sebagai pemegang kebijakan makro dengan menyusun regulasi, menyediakan kerangka etis, serta mendorong penguatan kapasitas institusi pendidikan agar mampu beradaptasi secara sehat dengan perkembangan teknologi.
Tanpa dukungan negara, upaya kampus dan kesadaran mahasiswa akan berjalan setengah hati. Tetapi dengan sinergi yang kuat antara ketiganya yaitu negara sebagai pengarah, kampus sebagai pelaksana, dan mahasiswa sebagai pelaku, AI bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan, bukan merusaknya.
Akhirnya, perlu kembali pada pertanyaan mendasar yaitu bukan sekadar apa yang bisa dilakukan AI untuk pendidikan, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa pendidikan tetap membentuk manusia yang berpikir, bukan sekadar pengguna teknologi. AI hanyalah alat. Nilai dari pendidikan terletak pada bagaimana manusia menggunakannya dengan akal sehat, hati nurani, dan tanggung jawab bersama.